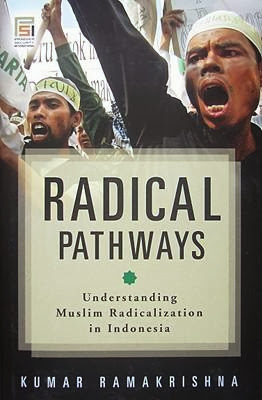 |
| Radical Pathways, Kumar Ramakrishna, 2009 |
Adhe Nuansa Wibisono, S.IP
Kajian Terorisme dan Keamanan Internasional UI
Jakarta, Senin 23 September 2013
Sumber Utama : Kumar Ramakrishna, “Radical Pathways : Understanding Muslim Radicalization In Indonesia”, (Connecticut, Praeger Security International, 2009)
Dimensi Budaya
Kumar Ramakrishna dalam “Radical Pathways : Understanding Muslim Radicalization In Indonesia” memaparkan pendekatan mengenai Radical Pathways Framework yang menggunakan pendekatan dimensi sosial budaya dari Geert Hofstede, antropologis, kulturalis dan peneliti sosial terkemuka dari Belanda. Argumen utama yang dibangun dalam Radical Pathways adalah radikalisasi terjadi ketika individu menderita penguatan kecemasan eksistensial atas identitas mereka. Kondisi ini terjadi ketika identitas dan budaya personal seseorang berinteraksi dengan faktor geopolitik, kekuatan sejarah lokal dan ideologi untuk membentuk rasa takut akan kehancuran kelompok. Dalam studi kasus anggota Jemaah Islamiyah, Darul Islam menjadi sangat sentral sebagai pusat ideologi yang tidak hanya menyediakan sistem kepercayaan bersama dan kohesivitas diantara pengikutnya, tetapi juga membangun pemahaman sebagai “korban sejarah” yang kemudian berkembang menjadi pandangan hidup “kita-melawan-mereka”. Konsekuensi untuk anggota JI kemudian adalah munculnya pemahaman dan aspirasi yang salah untuk memastikan bahwa ideologi radikal berlaku dalam kondisi apapun, termasuk pembunuhan warga sipil yang tidak bersalah.[1]
Geert Hofstede mendefinisikan kebudayaan sebagai “pemrograman kolektif pikiran yang membedakan anggota dari satu kelompok atau kategori kelompok dari yang lainnya”. Ia menambahkan bahwa gagasan kebudayaan sebagai “mental software” adalah pemahaman yang sering digunakan oleh sosiolog dan antropolog. Di sisi lain Gelfand, Nishii, Raver dan Lim menjelaskan pada level sistem struktural yang dimana faktor historis dan ekokultural tertentu menghasilkan peningkatan kebutuhan akan prediktabilitas dan aksi sosial yang terkoordinasi dengan budaya. Sebagai contoh, faktor seperti tingkat kepadatan populasi yang tinggi, kelangkaan sumber daya alam, suhu yang ekstrem, dan riwayat ancaman eksternal yang berhubungan dengan kebutuhan untuk menciptakan struktur sosial untuk memfasilitasi ketertiban dan aksi yang terkoordinasi dengan lingkungan sosial.[2]
Faktor sistemik kemudian dengan kuat membentuk struktur situasi yang terdiri dari konteks budaya atau lokalitas geografis. Sejumlah hambatan ekologis membentuk “situasi kuat”, sementara lingkungan lain mendorong “situasi lemah”. Situasi kuat membentuk ketertiban dan aksi sosial terkoordinasi dengan memiliki sejumlah norma yang jelas, dengan adanya sejumlah pola perilaku yang dapat diterima, dan dengan meningkatkan kecendrungan untuk mencela perilaku yang tidak tepat dan menyimpang. Di sisi lain, situasi yang lemah hanya memiliki sedikit norma yang jelas, memungkinkan sejumlah luas perilaku yang diterima, dan mampu menghargai berbagai pilihan perilaku individu. Kesimpulannya adalah individual dalam sistem kebudayaan “disosialisasikan untuk mengembangkan karakteristik psikologis sosial” yang dibutuhkan dalam membuat mereka “berfungsi secara efektif dalam situasi khas yang membentuk kebudayaan kelompok mereka”.[3]
Proses radikalisasi muslim di era modern di Indonesia seharusnya tidak mengabaikan lingkungan budaya – kebersamaan, cara belajar dan berpikir, kemampuan potensi dan merasakan. Menurut Hofstede, terdapat tiga dimensi dari kebudayaan nasional yang relevan dengan penjelasan mengenai radikalisme : power distance (jarak kekuasaan dari kecil hingga besar), collectivism versus individualism, dan uncertainty avoidance (penghindaran ketidakpastian dari lemah hingga kuat). Pemaparan ini membutuhkan penjelasan lebih mendalam, yaitu : (a) Power distance, sejauh mana anggota yang kurang kuat kolektivitas sosial-nya berada dalam masyarakat yang “mengharapkan dan menerima bahwa kekuasaan didistribusikan secara tidak merata”, (b) Collectivism, prinsip pengorganisasian masyarakat dimana “orang yang sejak lahirnya telah berintegrasi dengan kelompok yang kohesif dan kuat, yang terus melindungi mereka dalam pertukaran dengan loyalitas yang tidak perlu diragukan, (c) Uncertainty avoidance, “sejauhmana para anggota dalam suatu kebudayaan merasa terancam oleh situasi yang ambigu dan tidak dikenal”.[4]
Dalam masyarakat dengan jarak kekuasaan yang besar, baik masyarakat yang berpendidikan tinggi maupun rendah cenderung untuk menampilkan “nilai-nilai otoriter”. Ini berarti bahwa kelas bawah tergantung kepada elite kekuasaan untuk menyediakan jaminan sosial, harmoni dan ketertiban umum. Orangtua mengajari anak mengenai kepatuhan, menghargai orangtua dan keluarga yang lebih tua adalah kebaikan dasar seumur hidup, dan guru dihargai sebagai “orang yang memberikan kebijaksanaan pribadi” yang secara aktif membentuk “jalur intelektual” sang murid. Hofstede mengamati bahwa dalam masyarakat dengan jarak kekuasaan yang besar, terdapat “pola ketergantungan kepada senior yang meliputi semua kontrak sosial manusia, dan mental software yang berisikan kebutuhan yang kuat akan ketergantungan tersebut.[5]
Dalam masyarakat kolektif, individu tumbuh dalam jaringan sosial yang dibangun oleh tetua yang dihormati yang memberikan isyarat dalam sikap, kepercayaan dan nilai yang tepat dan tetap teguh dalam menjaga kelestarian harmoni. Dalam masyarakat kolektif, pendapat personal “tidak berlaku –ini sangat dipengaruhi oleh kelompok”. Pada faktanya, individu dalam masyarakat kolektif sejak masa muda mencoba untuk mempelajari keahlian dan sikap yang dapat memungkinkan dia mendapatkan apresiasi dan penerimaan dari kelompok. Dalam masyarakat individual, seseorang yang melanggar aturan sosial akan merasa bersalah berdasarkan kesadaran moralitas yang dikembangkan secara individual. Pada sisi lain, individu pada masyarakat kolektif yang melanggar aturan sosial cenderung untuk tidak merasa bersalah melainkan malu – berasal dari rasa kegagalan pribadi dalam memenuhi kewajiban kolektif yang secara luas dirasakan. Ini menjelaskan mengapa konsep “wajah” menjadi konsep yang sangat penting dalam masyarakat kolektiv – rasa harga diri yang berasal dari pemahaman bahwa dirinya memiliki hubungan yang baik dengan lingkungan sosial.[6]
Dimensi ketiga adalah penghindaran ketidakpastian, semua masyarakat manusia akan selalu menghadapi ketidakpastian, tetapi terdapat perbedaan nasional yang signifikan dalam menghadapi ambiguitas dan ketidakpastian. Perbedaan ini diekspresikan dalam semua ruang sosial. Misalnya, dalam masyarakat yang tingkat penghindaran ketidakpastiannya lemah, yang secara relatif nyaman dengan ketidakpastian dan ambiguitas, terdapat sejumlah peraturan untuk anak-anak mengenai hal-hal apa yang kotor, terlarang dan tabu, di sekolah siswa merasa nyaman dengan situasi belajar yang terbuka dan peduli dengan diskusi yang baik, sementara pendidik dapat mengatakan “saya tidak tahu” tanpa harus merasa gagal dalam tugasnya untuk mengajarkan pengetahuan. Di tempat kerja, ambiguitas dan kekacauan ditoleransi dan terdapat keyakinan akan generalis dan logika umum. Masyarakat cenderung untuk memiliki sedikit aturan, hukum-hukum umum dan kode tidak tertulis. Sebaliknya dalam masyarakat yang tingkat penghindaran ketidakpastiannya kuat, adalah masyarakat yang tidak menyukai ketidakpastian dan ambiguitas. Anak-anak disosialisasikan ke dalam aturan yang ketat mengenai hal apa yang dianggap kotor dan tabu, di sekolah para siswa lebih memilih situasi belajar yang terstruktur dan mencari “jawaban yang benar”, sementara para pendidik diharapkan memiliki jawaban tersebut. Di tempat kerja, adanya penekanan pada presisi dan formalisasi sebagaimana yang dimiliki para ahli beserta solusi teknisnya. Masyarakat secara keseluruhan memiliki aturan-aturan yang spesifik untuk mengatur perilaku sosial.[7]
Hofstede mengakui bahwa perilaku manusia merupakan produk bukan hanya kebudayaan tetapi paling tidak dua faktor lainnya yaitu sifat manusia dan kepribadian individu. Hofstede menganggap sifat manusia sebagai “tingkat universal dalam mental software seseorang” dan “sistem operasi” yang menentukan kemampuan manusia untuk merasakan “takut, marah, cinta, sukacita, kesedihan dan rasa malu”. Dengan kata lain, sifat manusia merupakan representasi dari manusia itu sendiri, terlepas dari latar belakang budaya, memiliki kesamaan dikarenakan evolusi bersama dari warisan biologis manusia. Sementara sifat manusia mewakili sesuatu yang universal, mewarisi sifat-sifat semua individu dimanapun di seluruh dunia, kebudayaan itu “dipelajari dan bukan bawaan” dan “khusus untuk kelompok atau kategori”. Pada akhirnya kepribadian dari individu adalah “seperangkat program mental unik yang tidak perlu dibagi dengan manusia lainnya”. Kepribadian seorang individu didasarkan pada ciri-ciri yang “sebagian diwariskan bersamaan dengan seperangkat gen unik individu dan sebagian lainnya dipelajari”. Pembelajaran dalam kasus ini berarti “dimodifikasi oleh pengaruh pemrograman kolektif” atau budaya dan “pengalaman personal yang unik”.[8]
Dalam Radical Pathways Framework, tiga elemen orisinal Hofstede yaitu Sifat manusia, Kebudayaan dan Kepribadian Individu telah dimodifikasi dalam beberapa hal. Lingkar terluar dari Radical Pathways Framework mewakili apa yang kita sebut sebagai Identitas Eksistensial – elemen dari Sifat Manusia yang sangat penting dalam memahami proses radikalisasi. Lingkar kedua dari variabel kebudayaan, dan inti dari konten framework disebut sebagai “Situated Individual Personality”. Pada intinya, Radical Pathways Frameworks menyebutkan bahwa dorongan utama manusia dalam proses radikalisasi adalah apa yang disebut sebagai Kecemasan Identitas Eksistensial – adalah produk dari Identitas Eksistensial, Kebudayaan dan merupakan seperangkat variabel Kepribadian Individu yang berinteraksi dengan faktor-faktor struktural seperti perkembangan geopolitik, kekuatan sejarah lokal, ideologi dan konteks kelompok kecil untuk “Situasi” lingkungan dari Kepribadian Personal tersebut. Pada dasarnya Radical Pathways Frameworkmenunjukkan bahwa interaksi istimewa dan unik dari elemen-elemen Identitas Eksistensial, Kebudayaan dan Situated Individual Personality dalam kehidupan setiap militan Jemaah Islamiyah menghasilkan Kecemasan Identitas Eksistensial. Kecemasan ini dibiaskan melalui prisma sejarah dan latar belakang kehidupan pribadi masing-masing individu, yang mencapai puncaknya pada berbagai tingkat proses radikalisasi individu.[9]
Analisa dan Kesimpulan
Melalui pendekatan Geert Hofstede dalam Radical Pathways Framework kita dapat melihat bagaimana dimensi sosial kebudayaan dapat berpengaruh dalam proses radikalisasi seseorang individu. Proses radikalisasi terjadi ketika individu menderita penguatan kecemasan eksistensial atas identitas mereka. Kondisi ini terjadi ketika identitas dan budaya personal seseorang berinteraksi dengan faktor geopolitik, kekuatan sejarah lokal dan ideologi untuk membentuk rasa takut akan kehancuran kelompok. Selain itu kita juga menemukan bagaimana tiga pendekatan Hofstede dalam memahami radikalisme yaitu power distance yang menjelaskan ketergantungan terhadap kelompok elite, collectivism yang menghasilkan keterikatan individu kepada kelompok sosialnya dan uncertainty avoidance dimana seorang individu memiliki kecemasan akan kebudayaan yang tidak dikenal.
Apa yang ingin dibangun oleh Hofstede sebenarnya sangat membantu dalam memahami proses radikalisasi yang terjadi pada anggota Jemaah Islamiyah di Indonesia. Bagaimana seorang anggota kelompok radikal yang terbiasa dengan mekanisme jarak kekuasaan yang besar pada kelompok sosialnya kemudian mendapati dirinya berada dalam masyarakat “sekuler” yang sama sekali berbeda. Problem akan kolektivisme juga dihadapi oleh kelompok radikal ini ketika mereka menghadapi paradigma demokrasi yang bersendikan kepada kebebasan, kesetaraan, dan hak asasi individu. Tentu saja terdapat jurang perbedaan yang sangat besar mengenai persepsi nilai, norma dan aturan sosial antara anggota kelompok radikal dengan masyarakat Indonesia secara umum. Kemudian ketidakpastian anggota kelompok radikal dalam kehidupan umum masyarakat Indonesia terutama dalam perbedaan akan tradisi nilai-nilai keagamaan, pandangan hidup, adat istiadat dan kebudayaan yang dianggap sekuler – yang dilihat sangat bertentangan dalam berbagai aspek kehidupannya.
Penulis menyarankan diperlukan adanya perumusan oleh para pemangku kepentingan, lembaga think tank dan pembuat kebijakan mengenai kebijakan seperti apa yang dapat meminimalisir perbedaan antara sejumlah kelompok sosial yang berpotensi mengalami proses radikalisasi di masyarakat. Kebijakan masyarakat terbuka (open society) yang mempertemukan antara banyak elemen dari masyarakat baik dari latar belakang agama, ras, budaya, tingkat sosial sehingga dapat meminimalisir munculnya radikalisme. Selain itu juga perlunya dirumuskan suatu kebijakan yang dapat meningkatkan keterlibatan kelompok-kelompok yang berpotensi mengalami radikalisasi dalam kehidupan publik di masyarakat, seperti akses pendidikan di sekolah negeri, komunikasi yang intensif dengan perangkat desa dan kelurahan, keterlibatan dalam acara-acara masyarakat seperti pernikahan, syawalan, buka puasa bersama, pengajian dan tabligh akbar terbuka. Jika memang ditemukan faktor kesenjangan sebagai penyebab munculnya radikalisme maka harus dirumuskan adaya sebuah kebijakan yang mampu menjamin distribusi sosial ekonomi yang merata di masyarakat sehingga kesenjangan ekonomi sebagai faktor radikalisme bisa diatasi.
Referensi
Kumar Ramakrishna, “Radical Pathways : Understanding Muslim Radicalization In Indonesia”, (Connecticut, Praeger Security International, 2009)
Terence Lee, “Radical Pathways: Understanding Muslim Radicalization in Indonesia(review)”, http://muse.jhu.edu/journals/csa/summary/v032/32.1.lee.html
[1] Terence Lee, “Radical Pathways: Understanding Muslim Radicalization in Indonesia (review)”, http://muse.jhu.edu/journals/csa/summary/v032/32.1.lee.html, diakses pada 23 September 2013
[2] Kumar Ramakrishna, “Radical Pathways : Understanding Muslim Radicalization In Indonesia”, (Connecticut, Praeger Security International, 2009), hal 19
[6] Ibid, hal 23

Recent Comments