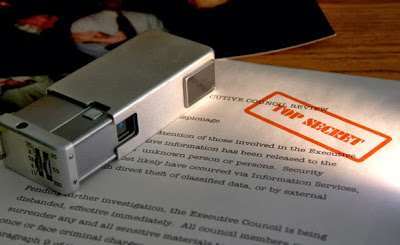 |
| Sumber gambar : http://www.mwebantu.com |
Adhe Nuansa Wibisono, S.IP
Kajian Terorisme dan Keamanan Internasional UI
Jakarta, Ahad 27 Oktober 2013
Sumber Utama : Geraint Hughes, “The Use of Undercover Military Units in Counter-Terrorist Operations : a Historical Analysis with Reference to Contemporary Anti-Terrorism”, Small Wars and Insurgencies, (London : Routledge, 2010)
Unit Intelijen dan Operasi Klandestin
Dalam artikel “The Use of Undercover Military Units in Counter-Terrorist Operations”, Geraint Hughes memberikan pemaparan mengenai unit penyamaran dan operasi klandestin di berbagai negara. Operasi klandestin dilakukan oleh intelijen negara asing dan juga dilakukan oleh perwira polisi yang melakukan penyamaran dan menyusup masuk ke dalam geng kriminal. Melalui operasi klandestin ini intelijen dikumpulkan ke dalam unit penyamaran dengan cara yang tidak menarik perhatian publik. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan cara pengawasan statis melalui pos pengamatan atau pengawasan mobile dengan operasi pelacakan tersangka teroris. Unit penyamaran militer juga dapat merekrut informan dari masyarakat sipil atau bahkan “merekrut” anggota dari kelompok teroris sehingga mereka bertindak sebagai mata-mata atau agen untuk negara. Kegiatan tersebut dilakukan secara rahasia dan tertutup agar tidak menarik perhatian dari kelompok teroris atau masyarakat sipil.[1]
Hughes kemudian menjelaskan perbedaan antara unit penyamaran dengan “kelompok pseudo” yang digunakan dalam kampanye kontra-terorisme sebelumnya adalah, kelompok pseudo direkrut untuk melakukan operasi “tidak sah”, yang mencakup serangan “false flag”, serangan yang dilakukan suatu unit penyamaran tetapi seakan-akan dilakukan oleh kelompok lainnya, dan juga pembunuhan politik terhadap musuh-musuh rezim. Praktik politik akan operasi pseudo meliputi kasus Selous Scouts di Rhodesia, kelompok anti-ETA, GAL (Grupos Antiterroristas de Liberacion) di Spanyol pada tahun 1980-an, dan pasukan pembunuh Vlakplaas/C10 yang aktif di Afrika Selatan selama tahun-tahun terakhir rezim apartheid berkuasa. Aktivitas kelompok pseudo ini baik secara etika dan strategi tidak dapat diterima dan kontra-produktif karena merusak kerangka hukum dimana legitimasi pemerintahan didasarkan.[2]
Tentara Inggris memiliki satu tradisi yang tetap dalam menggunakan “kelompok kontra” untuk melawan perang dalam peperangan dekolonisasi. Hal ini termasuk pula unit khusus bentukan Inggris, Special Night Squadsdi Palestina pada tahun 1937-1939, yang direkrut dari penduduk Yahudi lokal untuk melawan pejuang miltan Arab. Tentara Perancis juga menggunakan unit penyamaran barbouzes (jenggot palsu) di Aljazair pada tahun 1961-1962, setelah para perwira ekstrem kanan mendirikan Secret Army Organisation (OAS) dalam upaya untuk melakukan sabotase terhadap kebijakan Presiden Charles de Gaulle untuk memberikan kemerdekaan kepada Aljazair dan juga melakukan serangan balas dendam terhadap warga sipil Muslim.[3]
Setelah usaha yang gagal untuk menyelamatkan diplomat Amerika yang disandera di Iran pada April 1980, Angkatan Darat AS membentuk satu unit bernama Intelligence Support Activity (ISA) pada Januari 1981, meskipun sering mengubah namanya unit militer klandestin ini tetap aktif beroperasi. Selain itu Israeli Defence Force(IDF) telah menggunakan unit penyamaran untuk membunuh para pemimpin PLO di luar negeri (terutama tiga pemimpin operasi Black September dibunuh di Beirut pada April 1973) dan mereka juga menggunakan unit Mista’aravim (secara harafiah “menjadi Arab”) ke Tepi Barat dan Jalur Gaza untuk memburu militan Palestina.[4]
Unit klandestin telah terlibat baik dalam operasi domestik dan intervensi militer luar negeri yang melibatkan unit kontra-terorisme/kontra-insurgensi yang berada di luar negeri. Operasi ISA muncul terutama untuk terlibat dalam misi eksternal, seperti yang tercantum dalam Posse Comitatus Act(1878) yang mencegah militer AS dalam berpartisipasi dalam aktivitas kepolisian dalam negeri. Sebaliknya, militer Inggris memiliki tradisi yang mapan dalam memberikan “dukungan kepada kekuasaan sipil”, melakukan berbagai peran dari menjaga ketertiban umum hingga kontra-terorisme. Sebagai akibatnya unit penyamaran militer Inggris telah beroperasi baik di wilayah bekas koloni dan wilayah Inggris Raya.[5]
Hughes mencatat bahwa tingkat keamanan yang rendah dan inkompetensi seringkali menambah rumit permasalahan, di Aljazair unit penyamaran Perancis, Barbouzes, telah ditangkap dan dibunuh oleh OAS pada Januari 1962. Kesulitan untuk “menyatu” dan risiko akan kompromi yang ditunjukkan pada Insiden Basra pada September 2005. Sulit untuk menilai dampak dari bentrokan antara tentara Inggris dengan polisi dan masyarakat setempat di Jamiat, tidak menyebutkan tuduhan terhadap dua tentara yang mati (TV Iran menyebutkan bahwa mereka ditangkap akibat penembakan terhadap peziarah Syiah) – tapi insiden tersebut jelas merusak kredibiltas militer Inggris dengan Baswaris. Kasus ini menunjukkan bahwa misi penyamaran yang efektif di Irlandia Utara tidak mudah dilakukan di Iraq Selatan dikarenakan pihak keamanan setempat telah diinfiltrasi oleh kelompok kriminal terorganisir dan gerilyawan.[6]
Penggunaan unit klandestin juga menimbulkan masalah komando, kontrol dan akuntabiltas. Birokrasi pemerintahan bertentangan dengan peran, prosedur, dan garis tanggung jawab administratif departemen, dan keterlibatan tentara dalam aktivitas penyamaran seringkali menimbulkan sentimen dari polisi dan dinas intelijen domestik yang secara tradisional menjadi tugas mereka. Perwira militer reguler juga dapat curiga terhadap perwira dalam unit penyamaran, menganggap mereka sebagai pelanggar disiplin. Operasi mereka juga perlu diatur dan diawasi untuk mencegah peristiwa bentrokan antara unit klandestin dengan perwira polisi dan militer berseragam.[7]
Pertimbangan juga harus diberikan kepada posisi informan dan agen yang direkrut oleh unit militer klandestin. Terdapat dilema etika yang keras dalam perekrutan teroris sebagai agen, yang dimana anggota teroris harus tetap aktif agar dapat menjadi aset intelijen yang efektif. Agen yang “menyebrang” memainkan peranan penting dalam membatasi aktivitas teroris, satu sumber IDF menyatakan pada Agustus 2002 bahwa 80 persen serangan teroris dapat digagalkan dikarenakan laporan intelijen yang diberikan oleh informan. Meskipun demikian antara tahun 1988 dan 1993 sekitar 1000 orang yang diduga sebagai “mata-mata” telah dieksekusi oleh sesama orang Palestina, dan lebih banyak lagi yang menerima resettlement oleh IDF.[8]
Kegagalan Intelijen
Stephen Marrin dalam artikel “Preventing Intelligence Failures by Learning from the Past” bahwa “kegagalan” terjadi di setiap jalur, dari hal-hal yang sepele hingga pada hal-hal yang sangat penting, terjadi setiap hari karena berbagai alasan, termasuk kegagalan untuk mengumpulkan informasi yang relevan karena kesalahan prioritas dalam sistem pengumpulan data, analisis yang terburu-buru dan asumsi yang tidak dapat diterapkan.[9] Setelah itu Marrin menunjukkan pendapat Robert Wohlstetter dalam “Pearl Harbor : Warning and Decision”, yang mengatakan bahwa kejutan akan serangan bukan terjadi karena kekurangan data intelijen yang relevan namun seringkali diakibatkan karena kesalahan persepsi dari informasi yang tersedia.[10]
Mantan Direktur Central Intelligence Agency (CIA), Robert M. Gates merekomendasikan “lebih banyak interaksi, umpan balik dan arahan untuk prioritas strategi sebagai persyaratan untuk performa dan kinerja intelijen yang lebih baik”. Selain itu Anne Armstrong mencatat dalam sebuah artikel intelijen tahun 1989, bahwa “akhirnya pejabat intelijen harus dipandu oleh kebutuhan kebijakan dibandingkan pencarian informasi untuk kepentingannya sendiri”. Ia kemudian menyimpulkan bahwa tidak tersambungnya intelijen dan kebijakan dengan mengamati bahwa “strategi untuk memperpendek jarak diantara intelijen dengan kebijakan memiliki risiko tertentu untuk integritas para aktor terkait, walaupun begitu risiko itu tetap harus diambil”.[11]
Robert Jervis dalam “Reports, Politics, and Intelligence Failures: The Case of Iraq” mengatakan bahwa kegagalan intelijen terjadi karena ketidaksesuaian antara perkiraan dan informasi apa yang kemudian menjadi kenyataan. Hal ini menjadi penting karena para pembuat kebijakan dan masyarakat mempertimbangkan bahwa kebijakan didasarkan pada penilaian yang akurat, sehingga ketepatan informasi merupakan hal yang sangat penting.[12] Robert Jervis kemudian menjelaskan bahwa intelijen merupakan permainan antara “yang bersembunyi” dan “sang pencari”. Desepsi informasi cukup mudah dilakukan dan dapat mempengaruhi keakuratan nilai sebuah informasi.[13]Jervis kemudian mengambil contoh kegagalan intelijen AS dalam kasus kesalahan informasi senjata pemusnah massal Iraq. Ia menyebutkan tiga hal yang menjadi penyebab kegagalan intelijen dalam kasus tersebut, yaitu : (1) Terlalu banyak kepastian informasi, (2) Tidak adanya penjelasan alternatif, dan (3) Kurangnya imajinasi untuk memprediksi informasi.
Terlalu banyak kepastian informasi, laporan dengan jelas mencatat bahwa banyak penilaian intelijen AS dilakukan secara berlebihan, yang mengatakan bahwa Iraq memiliki senjata pemusnah massal yang tidak memiliki bukti yang cukup sehingga informasi itu layak untuk diragukan. Akibatnya intelijen mengatakan bahwa bukti yang ada hanya cukup untuk mengajukan Saddam Hussein dalam gugatan perdata tetapi tidak dalam tuntutan pidana. Pada tahun 2002, National Intelligence Estimate (NIE) dibuat dengan sangat terburu-buru, bahkan Presidential Daily Briefs (PDB) terlihat lebih mencolok, dikarenakan informasi yang didapatnya berasal dari berita-berita terbaru yang miskin akan konfirmasi dan analisis. Argumen lain untuk problem kepastian informasi berlebih ini adalah ketika para analis terlalu bergantung dan percaya kepada sejunlah sumber informasi independen dan mereka gagal untuk mempertimbangkan signifikansi dari laporan negatif dan tidak adanya bukti-bukti yang memperkuat informasi tersebut.[14]
Tidak adanya penjelasan alternatif, kegagalan berikutnya adalah kurangnya pertimbangan untuk melihat informasi dan penjelasan alternatif. Laporan dokumen yang ada menyebutkan apakah Iraq secara diam-diam melakukan impor tabung alumunium yang mengindikasikan bahwa Iraq membangun kembali program nuklirnya dan adanya fakta informasi adanya program perangkat lunak yang diperoleh Iraq untuk Unmanned Aerial Vehicles (UAV), termasuk juga peta Amerika Serikat yang secara tersirat menunjukkan ancaman terhadap Amerika Serikat. Selain itu juga muncul keraguan terhadap validitas dan akurasi informasi seorang informan yang disebut dengan “Curveball” yang mengatakan bahwa Iraq memiliki teknologi untuk memproduksi senjata biologis. Tapi kemudian yang menjadi perhatian adalah tidak adanya penjelasan alternatif mengenai perilaku dan kebijakan yang diambil oleh Saddam Hussein. Tidak adanya “Tim Merah” yang melakukan analisis dan kritik terhadap informasi mainstream yang berkembang, tidak ada analisis yang bertugas sebagai “Devil’s Advocate” untuk mengungkap sisi-sisi lemah dari informasi tersebut, dan tidak adanya analisis yang memperkirakan kemungkinan-kemungkinan lainnya.[15]
Kekurangan daya imajinasi, kekurangan daya imajinasi telah ditunjukkan oleh keengganan intelijen AS untuk memikirkan aspek-aspek yang membingungkan dalam perilaku politik Iraq. Seandainya intelijen bertanya mengapa Saddam Hussein menolak seluruh cara yang bisa dia lakukan untuk menghindari perang, akan didapatkan sebuah informasi yang tepat dan relevan dalam proses pengambilan kebijakan. Setelah perang, terdapat sebuah informasi yang mengatakan bahwa Perancis dan Rusia telah mengatakan kepada Saddam Hussein bahwa mereka akan menahan laju intervensi militer AS, dan informasi ini cukup berpengaruh dalam keputusan yang diambil oleh Saddam (dan jika negara-negara ini percaya bahwa Washington akan menarik kembali keputusannya, ini mungkin merupakan kesalahan paling fatal dari kegagalan intelijen). Melakukan analisis terhadap sikap perlawanan yang diambil Iraq dan mengkombinasikannya informasi intelijen tentang perilaku dan perkataan diplomat Perancis dan Rusia, akan dapat menyebabkan intelijen untuk memikirkan kemungkinan ini.[16]
Analisa dan Kesimpulan
Penggunaan unit intelijen baik yang berbentuk unit penyamaran, kelompok pseudo ataupun kelompok kontra telah lazim digunakan oleh berbagai negara untuk mendukung keberhasilan dalam sebuah operasi politik dan militer. Permasalahan akuntabilitas kinerja intelijen kemudian menjadi dilema yang berkembang dalam ruang-ruang demokrasi, dikarenakan tidak adanya pertanggungjawaban secara publik dan terbuka apalagi terkait dengan misi-misi politik yang rahasia, ilegal dan di luar hukum. Meskipun demikian penggunaan unit intelijen cukup memberikan signifikansi dalam strategi kontra-terorisme ataupun kontra-insurgensi, yang dimana unit intelijen dapat melakukan fungsi-fungsi seperti pengumpulan informasi mengenai strategi lawan, pengaburan informasi yang diteruskan kepada pihak lawan, perumusan rekomendasi kebijakan politik dari informasi yang didapat, penggagalan dan penangkalan rencana serangan yang akan dilakukan lawan dan infiltrasi ke dalam organisasi lawan dan melakukan strategi penangkalan dari sana.
Meskipun unit intelijen yang melakukan proses infiltrasi memiliki peranan yang sangat penting dalam berbagai proses pengumpulan informasi dan perumusan kebijakan tetapi hal itu bukannya tanpa resiko. Inkompetensi yang dimiliki unit intelijen akan berakibat kepada kegagalan sebuah operasi intelijen, penangkapan terhadap agen intelijen tersebut dan eksekusi mati terhadap intelijen yang tertangkap. Hal tersebut memberikan konsekuensi politik yang besar terhadap negara asal intelijen jika kegagalan tersebut terungkap kepada publik melalui media massa dan kemudian memiliki impilkasi politik yang besar terhadap stabilitas hubungan antar negara-negara terkait. Kesalahan dan ketidaktepatan informasi intelijen juga dapat memiliki konsekuensi politik yang negatif seperti yang terjadi dalam kasus kegagalan intelijen AS dalam kasus informasi senjata pemusnah massal di Iraq, yang sampai saat ini tidk pernah terbukti kebenarannya. Padahal argumen adanya senjata pemusnah massal itu menjadi alasan utama yang digunakan AS untuk melakukan invansi militer ke Iraq pada tahun 2003, sebuah tindakan pelanggaran hukum yang seharusnya dapat membuat AS dapat diajukan kepada mahkamah internasional atas pelanggaran HAM.
Untuk meminimalisir kegagalan intelijen yang seringkali terjadi maka ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mengurangi tingkat kegagalan tersebut, diantaranya adalah : (1) adanya proses konfirmasi dan rekonfirmasi terhadap informasi yang didapatkan intelijen untuk mengurangi tingkat kesalahan informasi, (2) dilakukan sebuah analisis kritik yang melakukan prediksi-prediksi alternatif terhadap infomasi yang didapat, (3) meningkatkan ketersambungan (interconnectivity) antara unit intelijen dan pengambil kebijakan agar dapat menghasilkan kebijakan politik yang tepat dan relevan, dan (4) meningkatkan interaksi melalui umpan balik (feedback) terhadap informasi yang tersedia untuk meningkatkan kinerja intelijen. Terakhir kemudian saya melihat bahwa proses akuntabilitas dan transparansi politik atas unit intelijen menjadi juga sangat penting dilakukan sesuai dengan semangat demokrasi yang ada. Diharapkan dengan adanya akuntabilitas intelijen, politisasi dan penyalahgunaan wewenang intelijen pun dapat diminimalisir, semoga.
Referensi
Hughes, Geraint, “The Use of Undercover Military Units in Counter-Terrorist Operations : a Historical Analysis with Reference to Contemporary Anti-Terrorism”, Small Wars and Insurgencies, (London : Routledge, 2010)
Jervis, Robert, “Reports, Politics, and Intelligence Failures: The Case of Iraq”, The Journal of Strategic Studies, Vol. 29, No. 1, 3 – 52, (New York : Routledge, February 2006)
Marrin, Stephen, “Preventing Intelligence Failures by Learning from the Past”, International Journal of Intelligence and Counter Intelligence, Vol.17, No.4, (New York : Taylor & Francis, 2004)
[1] Geraint Hughes, “The Use of Undercover Military Units in Counter-Terrorist Operations : a Historical Analysis with Reference to Contemporary Anti-Terrorism”, Small Wars and Insurgencies, (London : Routledge, 2010), hal 564
[9] Stephen Marrin, “Preventing Intelligence Failures by Learning from the Past”, International Journal of Intelligence and Counter Intelligence, Vol.17, No.4, (New York : Taylor & Francis, 2004), hal 657
[12] Robert Jervis, “Reports, Politics, and Intelligence Failures: The Case of Iraq”, The Journal of Strategic Studies, Vol. 29, No. 1, 3 – 52, (New York : Routledge, February 2006), hal 10

Recent Comments